Seutuh layang-layang talinya dipenggal ranting. Kepala layangan pun kehilangan kesadarannya. Dia terbang tanpa berpikir apa dan tanpa merasa menjadi apa. Wuzzz….fiuuuuw…zzzzzz….
Ketaksadaran lalu mengembalikan layang-layang ke ranting yang tadi membuatnya tak utuh. Ketika tersangkut di pucuk ranting, layang-layang mendapat kesadaran baru, “Hei, aku bagian dari pohon mangga! Tapi…tapi aku ini apanya, ya? Daun, ranting, buah, atau…apa?”
Layang-layang mengamati setiap bagian pohon mangga. “Mungkin saja aku daun,” duganya, “aku ‘kan punya tubuh pipih dan ringkih.” Lalu layang-layang merasa menjadi daun.
Angin berhela lagi dan lagi. Meniup siang, meniup malam, meniup siang yang lain lagi lalu malam yang lain lagi. Angin pun meniup hijau yang melapisi daun, mengamplas kilaunya, lalu menceraikannya dengan ranting. Setelah semua daun ranggas, layang-layang yang merasa menjadi daun bertanya-tanya, “Kapan giliranku? Kenapa aku tidak mengering dan gugur, ya? Atau…jangan-jangan aku bukan daun. Mungkin….mungkin aku ranting. Iya, betul. Aku ‘kan punya rangka kayu. Aku pasti ranting.” Lalu layang-layang merasa menjadi ranting.
Angin berhela lagi dan lagi. Meniup musim gugur jadi semi. Semi yang menyentuh ranting hingga bertunas. Ketika semua ranting menyembulkan kehidupan baru, layang-layang yang merasa menjadi ranting bertanya lagi, “Kapan giliranku? Kenapa cuma aku yang tak bertunas sama sekali?” Sejak saat itu, setiap angin yang berhela membuat layang-layang merisaukan kediriannya.
Tunas makin dewasa. Jadi daun dan jadi mangga. Lalu pada suatu hari seorang anak memanjat pohon dan memetiki mangga-mangga gendut yang bergayutan di sana. Saat melihat layang-layang yang saat itu tidak merasa menjadi apapun, si anak berhenti sebentar. Diamatinya layang-layang lalu dipetiknya juga.
“Aku tahu sekarang! Aku pasti mangga!” sorak layang-layang. Dalam dekapan si anak, di antara sekumpul mangga, layang-layang merasa menemukan kedirian baru.
Begitu sampai di rumah, si anak langsung membawa hasil petikannya ke dapur. Diletakannya mangga-mangga tersebut di balai-balai, di sebelah ibunya yang sedang memotong kentang.
“Mangga ini bisa untuk suguhan buat Bu de, Dik, lumayan juga,” kata si ibu.
Serampung memotongi kentang, ibu segera mencuci mangga-mangga itu bersih-bersih dan mengupasnya.
Sementara itu, layang-layang yang merasa mangga juga dibiarkan begitu saja rebah di balai-balai.
“Hei! Aku kok tidak ikut dicuci? Kalau semua mangga dikupas, kenapa aku tidak? Kenapa aku dibedakan dengan mangga-mangga lainnya?” protes layang-layang.
Ibu tidak menanggapi. Ia malah menggolekkan mangga-mangga yang telah dikupas, kuning dan basah, di piring lebar. Layang-layang, pucat dan kering, mulai ragu dirinya mangga. Dia tergolek di balai-balai dekat pintu dapur. Angin sore berhela-hela, menampari layang-layang yang punya kesadaran tapi tak punya kedirian. Layang-layang pun jadi terisak, “krepekrepekrepek….krepekrepekrepek….” tubuhnya yang dingin bergeletaran tanpa keteguhan.
Matahari dibenamkan angin dan isak layang-layang semakin hebat. Ketika itulah si anak datang membawa benang gelasan. Dihampirinya layang-layang, lalu disentuhnya hati-hati. Saat si anak mulai melilitkan benang gelasan pada rangka layang-layang, isak layang perlahan berhenti. Ketika hari lelap, layang-layang terjaga mencari. Perlahan layang-layang menemukan sebetuk keutuhan menjadi.
Keesokan paginya, si anak membawa layang-layang ke tanah lapang. Di sana layang-layang dilempar ke udara, dipercayakan kepada angin, lalu dibiarkan terbang meliuk-liuk. Menari-nari. Melintas atap rumah, melintas pohon mangga yang selama bermusim-musim menopangnya.
Pada titik tertinggi, ketika layang-layang dapat melihat bumi secara luas, sebuah kesadaran dan kedirian memeluknya utuh. Angin mencoba menampar layang-layang lagi, tapi kali ini layang-layang menentangnya dengan berani, “Aku tahu sebuah kata baru yang sangat aku, Ngin, ‘melayang’! Aku sudah tahu siapa aku.”
Layang-layang kali ini punya keyakinan cukup untuk menggulung angin….wuzzz…fiuwww…zzzz….
Sundea


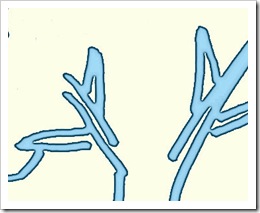
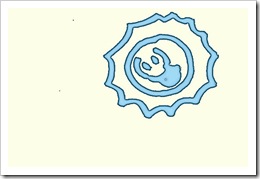
Komentar