Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa
Posting pertama di Salamatahari edisi ini bukan “inti matahari”. Bukan juga diambil dari sebuah event yang up to date. Tetapi tuhan tak pernah basi. Ia tak berakar, tak berpucuk, seperti tajuk pameran Handi Wirman di Galeri Nasional bebeberapa bulan silam …
“Hai, Dea,” sapa monumen tuhan ketika Dea lewat di hadapannya. Warnanya putih. Ia lebih besar daripada tuhan yang pernah Dea temui di mana pun.
“Jangan heran. Namanya juga monumen, jadi pasti dibuat lebih mencolok daripada yang asli,” sambung monumen tuhan seakan menangkap isi pikiran Dea.
Dea menanggapinya dengan senyum. Menyentuh simpul pitanya yang kaku. “Bagaimana rasanya menjadi monumen tuhan?” tanya Dea.
“Hmmm … rasanya seperti menjadi selebritis di dalam layar kaca. Tidak nyata. Hanya proyeksi bergerak dari sosok yang sesungguhnya,” jelas monumen tuhan.
“Tapi selebritis di layar kaca kan nggak bisa diajak ngobrol, kamu bisa.”
“Dea, kamu lupa, ya, kalau acara televisi bisa interaktif juga?”
Tuhan dan Dea terlibat pembicaraan yang tak berakar, tak berpucuk, tetapi menyenangkan. Ia yang biasanya mengapung di sungai-sungai jadi punya waktu untuk lebih dikenali melalui monumennya.
“Ketika ikut mengalir bersama sungai, sebetulnya kamu mau ke mana?” tanya Dea.
“Kenapa kamu yang tanya? Bukannya aku hanya mengantarkan pesanmu?”
***
Diam-diam, di seberang, mengintai monumen tuhan hitam yang bertajuk “Tak Berakar, Tak Berpucuk no.3” .
“Apakah dia musuhmu?” Dea berbisik-bisik pada monumen tuhan putih.
“Di adalah aku yang lain.”
Cahaya dan bayangan bertumpu pada satu obyek yang sama. Mungkin karena itulah tak ada “Tak Berakar, Tak Berpucuk no.1”.
Tuhan adalah esensi yang sensitif. Dengan menyentuhnya, kita belajar mengerti dengan merasa.
Tanpa berusaha mencari akar, tanpa berusaha mencapai pucuk.
Sundea
*judul pameran Handi Wirman yang Dea lupa tanggalnya =p






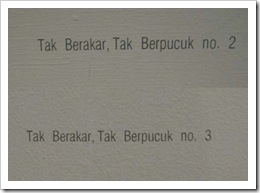
Komentar